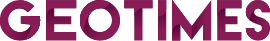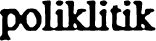Peresepan, penjualan, dan konsumsi antibiotik dianggap telah menjadi urgensi baru di Indonesia. Hal ini dipicu oleh banyaknya penggunaan antibiotik oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan rekomendasi dokter. Akibatnya, hal ini meningkatkan angka resistensi antimikroba (AMR) di dunia kesehatan. Berdasarkan data WHO terjadi peningkatan penggunaan antibiotik sebanyak 91 persen di dunia selama periode 2000-2015, khususnya di negara-negara berkembang. Kenaikan ini membuat AMR menjadi salah satu dari 10 ancaman kesehatan global paling berbahaya di dunia.
AMR pada akhirnya mempersulit penyembuhan penyakit dan membuat biaya kesehatan pasien semakin tinggi.
Berangkat dari hal ini, One Health University Network (INDOHUN) bekerja sama dengan Pfizer Indonesia menyelenggarakan Webinar bertajuk #TUNTASBERITUNTASPAKAI: Kebijakan Peresepan dan Praktik Penjualan dan Konsumsi Antibiotik di Indonesia. Adapun webinar ini ditujukan untuk mengajak para akademisi, praktisi, klinisi, dan masyarakat umum untuk sadar, peduli, dan tergerak untuk berkontribusi dalam menekan laju kasus resistensi antimikroba di Indonesia.
Koordinator INDOHUN, Prof. dr. Agus Suwandono, MPH., Dr. PH., menyatakan, dalam menangani AMR, prinsip pendekatan One Health perlu dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait. Adapun prinsip pendekatan tersebut terdiri dari koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Pada praktiknya, pemerintah Indonesia, dijelaskan Agus, telah menetapkan kebijakan berupa Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di sejumlah rumah sakit Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan melalui Permenkes No.8 Tahun 2015 dan juga beberapa peraturan penggunaan antibiotik di luar rumah sakit.

Namun demikian, menurut Agus, penanganan AMR ini tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi diperlukan juga dukungan dari masyarakat.
“Kontribusi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan AMR sangat diperlukan. Khususnya dalam menggunakan antibiotik secara bijak, rasional berdasarkan resep dokter, dan tuntas sesuai petunjuk dokter. Sehingga, angka kesembuhan meningkat dan mencegah terjadinya resistansi,” jelasnya dalam webinar yang diselenggarakan sebagai bentuk peringatan World Antibiotic Awareness Week 2021.
Senada dengan Agus, Ketua Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) RI Periode 2014-2021, Dr.dr. Harry Parathin, Sp.OG(K), menyatakan, salah satu faktor pemicu AMR di Indonesia ialah banyaknya penjualan antibiotik tanpa resep. Tindakan yang kerap terjadi ini bertentangan dengan peraturan mengenai penjualan obat antibiotik, yakni UU Obat Keras tahun 1949. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa yang berwenang untuk meresepkan obat antibiotik hanyalah Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Hewan.
“UU Obat keras juga menyebutkan bahwa obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, mendesinfektasikan tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak. Selain itu, pada bungkus luar obat keras harus dicantumkan tanda khusus berupa kalimat ‘harus dengan resep dokter’,” jelas Harry. Adapun tanda ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 197/A/SK/77 tanggal 15 Maret 1977.

Untuk menghambat laju AMR, Harry menambahkan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Penatagunaan Antimikroba (PGA) yang didasari oleh Permenkes no. 8/2015.
Adapun Permenkes ini berisi tentang implementasi PPRA di rumah sakit yang bertujuan untuk meningkatkan kesembuhan pasien, mencegah dan mengendalikan resistansi antimikroba, menurunkan angka kejadian rawat inap berkepanjangan, dan menurunkan kuantitas pengguaan antimikroba.
Pada praktiknya, tim dari PGA akan membantu pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam menerapkan penggunaan antimikroba. Tim ini juga akan mendampingi dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dalam menetapkan diagnosis penyakit infeksi, memilih jenis antimikroba, dosis, rute, saat dan lama pemberian. Sementara, DPJP bertugas untuk menegakkan diagnosis infeksi bakteri, memberikan antimikroba sesuai dengan panduan pelayanan klinik, dan bekerja sama dengan tim PGA KSM dan tim PGA KPRA-RS.
Menurut Harry, efektifitas dari kehadiran tim-tim tersebut telah terbukti melalui data dari pengeluaran unit farmasi pada tahun 2019. “Penggunaan meropenem satu gram di RSDS, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo, pada bulan November 2019 mulai mengalami penurunan setelah diluncurkannya PGA pada bulan Oktober 2019. Selain itu, bakteri resistan terhadap karbapenem yang sebelumnya berada di angka 17.19% pada bulan Oktober 2019, turun menjadi 10.94% pada bulan November. Penurunan berlanjut menjadi 3.13% pada bulan Desember,” jelasnya.

Tak sekedar dari segi penjualan, menurut Guru Besar FKKMK Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Tri Wibawa, PhD, SpMK(K), pola pikir masyarakat yang mengandalkan antibiotik dalam pengobatan mandiri juga menjadi salah satu faktor permintaan antibiotik sangat tinggi.
Dalam hal ini, pasien menganggap antibiotik sebagai obat yang manjur untuk segala jenis penyakit, mulai dari demam hingga nyeri sendi. Bersamaan dengan itu, tersedianya antibiotik di apotek dan toko obat terdekat, bahkan warung serta tidak diperlukannya resep untuk membelinya menjadikan obat ini sebagai ‘andalan’ yang digemari masyarakat. “Selain mudah diperoleh, biaya yang dikeluarkan pun tidak banyak. Akibatnya hal ini memicu berkembangnya AMR di Indonesia,” ungkap Tri.
Berdasarkan hasil penelitian oleh Studi Protecting Indonesia from the Threat of Antimicrobial Resistance pada apotek dan toko obat di daerah perkotaan dan pedesaan Indonesia, diketahui, lini antibiotik yang diberikan pun tidak dibatasi. “Meskipun antibiotik lini pertama seperti amoksisilin dan kotrimoksazol yang paling banyak diberikan, ada kekhawatiran bahwa antibiotik lini kedua termasuk sefalosporin juga diberikan tanpa resep,”ucap Tri.
Dia menambahkan, kondisi tersebut pun diperparah dengan kurang memadainya petunjuk penggunaan antibiotik yang benar. “Hasil penelitian juga menunjukkan, konsultasi di toko obat seringkali tidak memadai. Seringkali antibiotik diberikan tanpa petunjuk penggunaan yang benar,” tambahnya.
Untuk mengatasinya, Tri mengatakan, perlu adanya penguatan implementasi regulasi untuk mengendalikan peredaran antibiotik di masyarakat. Di samping itu, secara bersamaan, pendekatan multi aspek juga perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong praktik penjualan antibiotik tanpa resep ini. “Seperti motivasi untuk memaksimalkan keuntungan dari toko-toko obat, tingginya permintaan antibiotik dari pelanggan, dan dorongan dari pemilik untuk bersaing dengan toko lainnya,” ujar Tri.